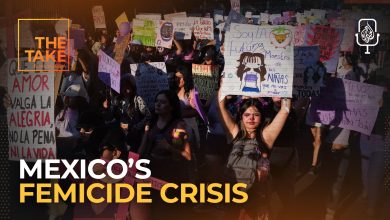Blog: Blog | Gaza: Apa yang harus dipikirkan saat Anda terlalu lelah untuk memikirkan perang

Sejak serangan Hamas yang mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan tanggapan militer Israel yang brutal di Gaza, kami telah dibanjiri dengan gambar -gambar perang: kota -kota yang dikurangi menjadi puing -puing, anak -anak yang ditarik dari puing -puing, rumah sakit kewalahan, dan keluarga hancur. Ini bukan hanya angka atau berita utama – mereka menangis dari jantung suatu wilayah dalam kekacauan tanpa akhir.
Jutaan video dan foto terus beredar, masing -masing lebih dahsyat daripada yang terakhir. Ketika pasukan Israel masuk kembali Gaza dengan semua senjata menyala, siklus berlanjut, memperdalam kelelahan kolektif kita. Bagi sebagian orang, gambar menjadi mati rasa; Bagi yang lain, sangat menyakitkan. Saya mengaku, saya adalah di antara mereka yang tidak bisa lagi menonton. Setelah lebih dari tiga dekade melaporkan dari zona konflik – yang mencakup serangan teror, pemboman bunuh diri dan kekerasan komunal – saya tahu bau perang, aroma darah di udara, pemandangan anggota tubuh yang tidak lagi menyerupai manusia yang pernah mereka miliki. Kenangan itu tidak pernah benar -benar meninggalkan Anda.
'Kelelahan perang'
Dan sekarang, menonton liputan Gaza tanpa henti, saya merasakan berat baru. Saya mulai membaca cerita tentang seorang anak di rumah sakit, atau seorang ibu yang mencari puing -puing, dan saya berhenti. Saya mencoba menonton video, hanya beberapa detik, dan saya mematikannya. Itu bukan ketidakpedulian. Ini semacam kesimpulan perang yang menggali ke dalam jiwa Anda. Bahkan jurnalis di garis depan bersaksi tentang kelelahan emosional ini. Itulah yang sekarang banyak disebut 'kelelahan perang'.
Ini bukan untuk berpaling dari penderitaan. Sebaliknya, saya sangat percaya dalam memberikan kesaksian. Tetapi semakin banyak, saya mendapati diri saya tertarik pada jenis cerita lain – yang berakar pada ketahanan, dalam hidup berdampingan dan, ya, dengan harapan.
Sebagian besar perhatian media dunia (dan memang demikian) difokuskan pada kehancuran di Gaza dan ekspansi agresif pemukiman Israel di Tepi Barat. Berita utama dipenuhi dengan perang, ekstremisme, dan perampasan. Tetapi di tengah -tengah api dan kemarahan ini, sebuah kisah yang lebih tenang juga sedang berlangsung, sedikit demi sedikit, betapapun tidak terlihat: Israel dan Palestina, warga negara Yahudi dan Arab di dalam Israel, dan beberapa kasus menumpahkan ke Tepi Barat yang diduduki, bekerja untuk membangun masyarakat bersama dan damai.
'Oasis of damai' di bukit
Enam tahun yang lalu, saya mengunjungi Israel dengan penugasan pelaporan. Di luar pekerjaan saya yang ditugaskan, saya mencari tanda -tanda koeksistensi damai, betapapun pingsan. Dan saya menemukan satu-di bukit antara Yerusalem dan Tel Aviv, di sebuah desa yang disebut Wahat al-Salam-Neve Shalom, secara harfiah berarti “Oasis of Peace.” Namanya hyphenated, sengaja, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Ibrani. Di sini, keluarga dari komunitas Muslim Arab dan Yahudi hidup berdampingan, bukan secara tidak sengaja, tetapi dengan desain.
Desa, didirikan pada tahun 1970 -an oleh kedua komunitas, mengelola sekolah bilingual dan pusat pendidikan perdamaian. Anak -anak belajar bersama, tidak hanya dari buku teks tetapi melalui pengalaman bersama – musik, tarian, bermain. Saya menyaksikan anak -anak Arab dan Yahudi bernyanyi dan menari dengan lagu -lagu Bollywood, tawa mereka tidak bisa dibedakan. Sulit untuk mengatakan siapa itu siapa, dan itu, mungkin, adalah intinya.
Bahkan sekarang, di tengah konflik yang memburuk, desa melanjutkan misinya. Orang tua, guru, dan anak-anak Wahat al-Salam berpegang pada sesuatu yang berharga: keyakinan bahwa kedamaian dimulai bukan pada perjanjian, tetapi di ruang kelas.
Lihat lebih dekat
Di tempat lain, inisiatif akar rumput – dari pusat budaya Arab -Yahudi di Haifa hingga organisasi sipil bersama di Jaffa dan LOD – berusaha mempertahankan benang koeksistensi yang rapuh. Ini bukan gerakan utama yang menarik perhatian. Tapi mereka nyata.
Ambil tangan, jaringan sekolah bilingual terintegrasi di seluruh Israel. Moto mereka sederhana: “Di Israel, Yahudi dan orang Arab hidup dalam pemisahan, ketakutan dan kekerasan. Kita sedang dalam misi untuk mengubahnya.” Mereka menyatukan anak -anak dan keluarga untuk belajar, berkomunikasi, dan dipahami. Dalam iklim hari ini, ini bukan hanya revolusioner, itu radikal.
Atau pertimbangkan Givat Haviva, sebuah organisasi masyarakat sipil yang didedikasikan untuk membangun masyarakat bersama melalui pendidikan, dialog, dan inisiatif masyarakat. Visi mereka berlabuh dalam saling menghormati, pluralisme dan kesetaraan intrinsik antara warga negara. Mereka bekerja di kota -kota di mana ketidakpercayaan berjalan dalam, namun tetap percaya pada kekuatan interaksi manusia sehari -hari untuk mengubah hati.
Upaya -upaya ini menghadapi peluang yang menakutkan. Organisasi -organisasi ini mengeluh bahwa angin politik di Israel semakin menjadi memusuhi gagasan koeksistensi. Kebijakan segregasionis, retorika nasionalis dan undang -undang yang diduga diskriminatif telah memperluas kesenjangan. Bagi banyak warga Arab Israel, kesetaraan penuh tetap agak sulit dipahami. Dan bagi banyak warga negara Yahudi, ketakutan – diperburuk oleh serangan seperti 7 Oktober – membiakkan rasa tidak aman dan kecurigaan.
Tapi bagaimana jika kita melihat lebih dekat? Di luar pos pemeriksaan, di luar pemukiman, di luar dinding?
Kisah Budrus
Lima belas tahun yang lalu, ada sebuah desa yang diam -diam membuat sejarah. Budrus, yang terletak di Tepi Barat yang diduduki, menjadi simbol dari sesuatu yang jarang terkait dengan wilayah ini: perlawanan tanpa kekerasan. Pada tahun 2003, ketika Israel mulai membangun penghalang pemisahan yang mengancam akan memutuskan desa dari kebun zaitun dan lahan pertaniannya, orang -orang Budrus memilih untuk tidak merespons dengan kemarahan atau roket – tetapi dengan tekad.
Minggu demi minggu, penduduk desa berkumpul dalam protes damai. Wanita dan gadis berbaris di garis depan. Anggota saingannya faksi Palestina, Fatah dan Hamas, berdiri bersama dalam persatuan yang langka. Dan di pihak mereka adalah aktivis Yahudi Israel, mempertaruhkan reaksi dari masyarakat mereka sendiri untuk bergandengan tangan dalam tangisan bersama untuk keadilan. Secara total, mereka mengadakan 55 demonstrasi selama 10 bulan dan, luar biasa, mereka menang. Pemerintah Israel menyulut kembali tembok, melestarikan akses ke 95% dari tanah desa.
Kemenangan yang tenang ini ditangkap dalam film dokumenter yang kuat, Budrus, diarahkan oleh Julia Bacha dari kelompok nirlaba Just Vision. Saya bertemu dengannya dan timnya di Washington DC tak lama setelah film mulai beredar melalui festival dan pemutaran pribadi. Palestina muda, bermata cerah dan orang Israel Yahudi duduk bersama, masih tersentuh oleh apa yang telah mereka dokumentasikan. Ketika ditanya mengapa timnya memilih cerita ini, Bacha menawarkan jawaban sederhana: “Orang-orang terus bertanya, di mana Gandhi Palestina? Mengapa Palestina tidak mencoba tanpa kekerasan?”
Gandhian Ahimsa
Tanggapannya adalah film itu sendiri – bukti fakta yang mereka miliki. Yang mereka lakukan. Bahwa di suatu tempat, di suatu daerah yang terlalu sering diratakan menjadi biner korban dan agresor, masih ada orang -orang yang percaya pada kekuatan keras kepala perlawanan damai. Mereka percaya pada Ahimsa – prinsip Gandhi non -kekerasan – bukan sebagai kemewahan moral, tetapi sebagai kebutuhan strategis.
Kisah Budrus menawarkan secercah apa yang mungkin terjadi. Penduduk desa kemudian bergabung dengan kampanye serupa di kota -kota lain. Untuk sesaat, rasanya seperti model yang bisa menyebar – kedamaian itu, betapapun rapuh, mungkin menular.
Tapi hari ini, setelah berbulan -bulan perang, harapan itu terasa jauh. Pembantaian oleh Hamas dan respons yang menghancurkan Israel telah memperdalam jurang. Filosofi Ahimsa merasa terpojok dan dikalahkan – kewalahan oleh kekuatan kekerasan dan retribusi semata -mata.
Namun, mungkin pada saat -saat paling gelap inilah kisah -kisah perdamaian yang paling penting. Bukan karena mereka menawarkan perbaikan cepat atau penebusan yang mudah, tetapi karena mereka mengingatkan kita pada sesuatu yang mendasar – bahwa bahkan ketika dunia dilalap api, orang masih dapat memilih cara lain. Sejarah menawarkan kepastian yang tenang. Perang yang dulu tampaknya tak ada habisnya sering memberi jalan untuk rekonsiliasi. Perang 'seratus tahun' yang disebut antara Inggris dan Prancis akhirnya memberi jalan bagi perdamaian dan kemitraan selama berabad-abad. Pada 1960 -an dan 70 -an, Amerika Serikat menjatuhkan gudang bom yang tidak terpikirkan di Vietnam, kota -kota dan desa yang menghancurkan, generasi jaringan parut. Namun, hari ini, orang Vietnam – sementara mereka tidak melupakan kengerian – telah memilih untuk bergerak maju. Ini bukan amnesia. Ini adalah tindakan kehendak, keputusan untuk hidup di luar reruntuhan.
Upaya lemah ini mungkin tidak mengakhiri perang. Mereka bahkan mungkin tidak membawa gencatan senjata. Tapi mungkin mereka bisa mengingatkan kita, dan mereka yang berkuasa, seperti apa kedamaian yang dulu, dan seperti apa rasanya lagi. Petisi untuk perdamaian tidak naif, itu adalah kebutuhan saat ini. Seperti yang pernah diingatkan oleh penyair perang bahasa Inggris, “Kita harus saling mencintai atau mati.” Pilihannya adalah milik kita. Bertahun -tahun perang belum membantu kami sejauh ini. Berikan kedamaian kesempatan.
(Syed Zubair Ahmed adalah jurnalis senior India yang berbasis di London dengan pengalaman tiga dekade dengan media barat)
Penafian: Ini adalah pendapat pribadi penulis